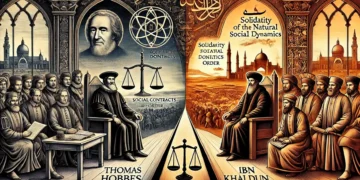Oleh : Try dan Ali Al-fatih
“Dari pada investor atau orang luar masuk kesini merusak (menambang), mendingan dirusak (Ditambang) oleh kita (Catatan Lapang Nasihin, 2016)”.
Tuturan ini mengambarkan bahwa pada persoalan pertambangan emas terjadi pertarungan antara orang lebak dengan orang diluar Lebak, bahkan dengan perusahaan bermodal besar. Ketiga kelompok ini, sama-sama memiliki kepentingan masing-masing, dengan segala daya yang mereka miliki. Penambang rakyat berkepentingan untuk mencari pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan perusahaan, menjalankan bisnis untuk memutar modal yang tidak menutupkemungkinan akan berdampak terhadap lingkungan dalam proses pengolahan hasil tambang. Seperti halnya, beberapa perusahaan tambang di wilayah lain, yang tidak mentaati aturan-aturan yang menyangkut kedalam peraturan lingkungan.
Keduanya berdampak pada keseimbangan alam, yang mengakibatkan tergerusnya tatanan ruang hidup yang sudah sekian lama terbangun. Yang membedakan antara tambang rakyat dan perusahaan tambang hanyalah pada persoalan luasan wilayah tambang dan pada soal legal saja.
Pertambangan rakyat, akan berdampak pada sebagian kecil lingkungan sekitar, karena luasan area yang ditambang bersekala kecil, hasil tambang kecil, bahan untuk pengolahan hasil tambang juga kecil. Namun, kegiatan tambang rakyat akan berdampak luas jika, limbah hasil olahan tambang dibuang kesuangai, yang akan mengalir jauh ke hilir sungai. Sama halnya dengan pertambangan rakyat, dampak yang diakibatkan oleh perusahaan tambang terjadi lebih massif, Cacat fisik, berkurangnya ikan di sungai-sungai dan di laut, matinya biota sungai dan laut dan lain sebagainya. Bahkan, bukan hanya pada perubahan alam semata.
Hadirnya perusahan berdampak juga pada soal-soal yang lebih dalam dari kesadaran orang kampung, salahsatunya adalah kepedulian untuk menjaga lingkungan menjadi luntur. Dengan kawasan tambang yang luas, bahkan dimungkinkan akan merambah pada lahan-lahan milik orang kampung hingga pada wilayah pemukiman. Sehingga hal-hal di atas sangat dimungkinkan terjadi.
Dalam hal ini, penulis membagi dua kelompok, distratifikasi dari perbedaan besaran modal, dan pengaruh ekspansi terhadap Ruang Hidup. Pertama, kelompok penambang rakyat dengan kekuatan modal dan politik struktur yang lemah. Sehingga, memiliki daya ekspansi yang lemah terhadap Ruang Hidup. Kedua, kelompok raksasa, yaitu Perusahaan tambang dengan kekuatan modal yang besar dan kekuatan politiknya yang besar. Sehingga, daya ekspansinya kuat dan besar terhadap Ruang Hidup.
Pertarungan ini sudah jelas akan dimenangkan oleh perusahaan, sebab memiliki daya yang sangat besar. Pada pihak lainnya, yang secara daya memiliki keterbatasan sudah barang tentu akan hengkang atau didepak secara sadar atau tidak. Pemodal besar, apalagi ditambah dengan perselingkuhan dengan penguasa, hanya akan melahirkan ekspansi kapital yang luas, mendalam, dan cepat. Orang Lebak, yang berprofesi sebagai penambang, petani, atau profesi lainnya, hanya akan mendapatkan kerugian secara sosial, ekonomi, ekologi dan kultural.
Diberbagai tempat, di mana terjadinya ekspansi kapital, hanya melahirkan keterdesakan pada suluruh aspek Ruang Hidup. Disadari atau tidak, ekspansi kapital, melalui pertambangan akan merampas satuan-satuan sosial ekologi yang menyejarah, satu-persatu, hingga titik nadir yang paling dalam pada tatanan Ruang Hidup secara struktural. Pada akhirnya, denyut jantung suatu tatanan Ruang Hidup berhenti berdegup, seperti yang terjadi di pulau “Kyushu” Jepang pada era 1950-an, yang mengakibatkan kepulauan tersebut tepatnya di desa “minamata” tidak layak dihuni oleh manusia dan binatang atau hewan.
Pertambangan emas begitu menggiurkan bagi sebagian Orang Lebak dan Perusahaan Tambang. Namun, dengan dampak negatif terhadap tatanan Ruang Hidup, apakah moda ekonomi ini akan terus dipertahankan. Hingga, Ruang Hidup Lebak tak lagi layak untuk dihuni, seperti desa “minamata” di kepulauan “Kyushu” Jepang.
Geologi Daerah Kabupaten Lebak
Kondisi Alam
Secara geologi Kabupaten lebak berada didalam koordinat 106ᵒ00’ – 106ᵒ30’ Bujur Timur dan 6ᵒ30’ – 7ᵒ00’ Lintang selatan. Luasan wilayah kabupaten lebak sekitar 2500 Km persegi. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, disebelah barat Laut Berbatasan dengan Kabupaten serang, di sebelah utara berbatasan dengan kabpaten bogor dan di sebelah timur laut – timur berbatasan dengan kabupaten sukabumi.
Musim hujan di kabupaten lebak, berlangsung dari bulan November hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau di kabupaten Lebak berlangsung dari bulan April hingga bulan Oktober. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun antara 2500 mm dan 3500 mm (Sandy, 1979. Dalam Lembar Geologi lembar Leuwidamar Indonesia, Sujatmiko dan S. Santosa, 1970). Kelembaban udara berkisar antara 74% dan 85% (Pusat Meteorologi dan geofisika Jakarta, 1980. Dalam Lembar Geologi lembar Leuwidamar Indonesia, Sujatmiko dan S. Santosa, 1970).
Binatang liar, yang masih terdapat di daerah Kabupaten Lebak, antara lain kucing hutan, babi hutan, rusa, kera dan jenis ungags. (Dalam Lembar Geologi lembar Leuwidamar Indonesia, Sujatmiko dan S. Santosa, 1970).
Bagian puncak gunung dan pegunungan di kabupaten lebak pada dasarnya tertutup hutan tropika dan hutan lindung. Bagian lereng gunung atau pegunungan dan perbukitan tertutup oleh hutan reboisasi, perkebunan, lahan pertanian, dan rerumputan. Daerah dataran dan lembah sungai merupakan pesawahan, lahan pertanian dan pemukiman. Pada tahun 1990 an di daerah gunung dan pegunungan, mulai terdapat aktivitas pertambangan rakyat. Pada tahun 2000 an di daerah dataran dan perbukitan mulai terdapat aktivitas pertambangan batubara.
Secara umum, batuan yang tersingkap di kabupaten lebak berumur Eosen hingga Resen, terbagi atas Endapan permukaan, Batuan Sedimen, Batuan Gunungapi, Batuan Terobosan, dan Batuan Metamorf.
Sumber Alam di Kabupaten Lebak
Di Kabupaten Lebak, terdapat sumber alam yang melimpah, berupan endapan mineral bijih, batubara dan komoditas untuk bahan bangunan.
Endapan Mineral Bijih – Sejak tahun 1954 hingga tahun 2010 unit pertambangan Emas Cikotok, perusahaan Negara (P.N) Aneka Tambang (dikenal dengan PT. ANTAM), menlakukan penambangan emas, perak, timbal, seng dan mineral bijih lainnya di daerah Banten Selatan, tepatnya di Kabupaten Lebak. penambangan tersebut merupakan penambangan lanjutan dari pertambangan Emas dan perak yang pernah di eksploitasi oleh pihak belanda, Jepang dan Suwasta sebelum tahun 1954. Eksplorasi dilakukan secara penambangan terbuka dan bawah tanah terhadap urat kuarsa yang terutama terdapat dalam Formasi Cikotok yang terpropiritkan dan batuan sedimen berumur Paleogen.
Daerah eksplorasi, terutama terdapat di Cikotok, Cirotan, Hateml, Lebak Sembada, Cipicung, Cikaret, Cimari, dan Pasir Malang.
Pabrik pengolahan permulaan terletak di Pasir Gembong, sedangkan pengolahan dan pemurnian selanjutnya dilaksanakan olen unit pengolahan dan pemurnian logam mulia, P.T. Aneka Tambang, di Jakarta. Hasil pengolahan dan pemurnian logam mulia dari PE Cikotok, adalah sebagai berikut :
1986 : 211 Au dan 2.368 Ag
1987 : 160 Au dan 3.609 Ag
1988 : 165 Au dan 2.819 Ag
Tahun 1940 an cadangan bijih Cikotok ± 700 ton, sedangkan cadangan teruji sebesar 569.041 ton bijih dengan kadar 8,4 gr Au per ton dan 481 gr Ag per ton. Sebelum tahun 1954, hasil produksi yang pernah dicapai adalah 61.096 ton bijih dengan kadar 10 gr Au per ton, dan 557 gr Ag per ton; hasil total 488.048 gram Au dan 25.558,388 gram Ag. Hasil produksi dari UPE Cikotok, P.N. Aneka Tambang, sejak tahun 1957 mengalami grafik turun naik. Selain mineral logam mulia juga dihasilkan konsentrat timbal dan seng.
Pasir besi-titan yang mengandung magnetit, titanomagnetit, mineral mafik dan mineral terang. Terakumulasi di pantai selatan di sebelah timur Cikotok. Lapisan pasir besi titan rupa sisipan dalam endapan teras sepanjang pantai Cibangban. Tebalnya sekitar beberapa puluh centi meter.
Batubara – Batubara terutama terdapat dalam formasi: Bayah, Cijengkol, dan Bojongmanik, berumur dari Eosen hingga Miosen. Cadangan yang cukup besar terdapat di daerah Bayah, Cimandiri, Leuwidamar dan Bojongmanik. Kini batubara tersebut telah diusahakan oleh pihak swasta sesuai dengan daerah konsesi yang telah ditentukan. Batubara dibagian selatan tersingkap di sekitaran Bayah dan Cimandiri berjenis bitumen dan tebal lapisan antara 0,6 m dan 2 m. lapisannya terputus-putus oleh sesar dengan sudut kemiringan 60ᵒ. Penambangannya dilakukan dengan system “tunnel” dan system “shaft” oleh pihak swasta atau perorangan. Cadangan batubara di daerah Cimandiri diperkirakan 6,2 juta ton. Dan di daerah Bayah sebesar 6,9 juta ton.
Batubara dibagian utara, terletak di sekitar Desa Bojongmanik, terdapat dalam Formasi Bojongmanik dengan kadar rendah dari jenis lignit. Lapisan batubara di sini tebalnya antara 0,3 m dan 2 m, dan terdiri dari beberapa lapisan atau lensa. Batubara dari Bojongmanik mengandung 14% resin, 60% coke, 10% NH3 dan 25% gas. Cadangan diperkirakan sekitar 7,4 juta ton.
Minyak Bumi – Adanya petunjuk perangkap minyak bumi berupa rembesan (“oil seep”), antara lain terdapat di sekitar Pasir Puspa S. Ciwana, di dalam batulempung lumpuran warna hitam dari Formasi Cimapag, dan di sungai Ciateulangi, banten selatan. Rembesan ini tidak ekonomis. Sampai saat ini, belum ada penelitian lebih lanjut terhadap minyak bumi ini.
Mata Air Panas – Beberapa mata air panas terdapat di sekitar Desa Cimanggoli dan Cisusuk, di sekitar G. Endut dan Cipanas dekat Cisolok, dengan suhu antara 30ᵒ dan 40ᵒ C. sedangkan, mataair panas di Cipanas dengan suhu 40ᵒ C lebih, dapat menyembur sampai beberapa meter tingginya. Kini, dimanfaatkan untuk tempat pariwisata yang dikelola oleh pemda setempat.
Bahan Bangunan – Batugamping dari satuan batuan berumur Oligosen hingga Miosen, dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan industry dan akan direncanakan untuk batu hias bangunan gedung seperti marmer dan ornamen.
Granodiorite, diorite kuarsa, dasit, batupasir kuarsa, tuf halus warna putih dari tuf malingping, tuf dasit dan kayu terkeraskan dari Formasi Genteng, cukup menarik untuk bahan bangunan dan batu hias atau ornamen.
Batuapi (“flintstone”) terdapat disekitar desa kerta dan Gn. Kendeng. Beberapa tahun kebelakan sedang di eksploitasi oleh pihak swasta. Hasil penambangannya sebagian besar dipasarkan ke Jakarta.
Bahan bangunan lainnya terdiri dari andesit, basalt, dasit, pasirkuarsa, endapan pantai, diorite kuarsa dan endapan sungai. Bahan-bahan ini, terdapat sangat melimpah. Biasanya, dipergunakan untuk fondasi gedung, bangunan, jembatan, dan bendungan, juga untuk pengerasan jalan.
Disekitar daerah kontak terobosan granodiorite Cihara, sering dijumpai batu permata (“gem stone”), seperti: kuarsa gunung, jasper, kalsedon, akik, amethis dan opal. Beberapa tahun silam, permata ini telah di eksploitasi oleh swasta dan perorangan untuk batu cincin, leontin dan hiasan lainnya, serta cendera mata.
Disekitar Desa Suwakan, dalam tuf Citorek terdapat tuf putih hingga hijau pucat, berbutir halus hingga sedang, sering mengandung mineral zeolite dari jenis klinoptilolit, mordenit dan natrolit. Mineral zeolite tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan penjernih air, pupuk, imbuhan makanan ternak, pengembangan makanan ternak dan lain sebagainya. Beberapa waktu silam telah di eksploitasi oleh pihak swasta sesuai dengan wilayah konsesinya yang telah ditetapkan. Eksplorasi, eksploitasi dan teknologi pengolahan terhadap mineral ini masih terus dikembangkan.
Perkembangan Tambang Emas Rakyat di Kabupaten Lebak
Sejak tahun 1990 an, orang-orang Lebak sudah mulai menambang emas dengan cara tradisional. Pertambangan emas, pada masa itu mulai menjadi pilihan pencaharian orang lebak. Sebaran ini terjadi di beberapa titik wilayah, diantaranya: wilayah kecamatan Cibeber, Cipanas, Cilograng dan Panggarangan pada awalnya. Namun, orang yang melakukan penambangan emas, bukan hanya warga sekitar saja, ada juga warga yang datang untuk menambang emas dari Kecamatan lain, bahkan dari luar wilayah Kabupaten Lebak, seperti Sukabumi. Pengetahuan penambangan emas dipengaruhi oleh pemerintah kolonial belanda pada masa penjajahan. Selanjutnya, lebih diperdalam oleh mantan pekerja PT.ANTAM dan warga pendatang dari Tasikmalaya.
Proses pengolahan hasil tambang, pada mulanya dilakukan dengan proses “gelundung” dengan alat penggerak aliran air, dengan alat tangkap “Kuik” atau “Mercury”. Seiring berjalannya waktu, pengolahan hasil tambang berkembang pada proses “Rendem” dengan bahan sianida (Cn). Moda ekonomi ini, pada akhirnya menjadi salahsatu ‘primadona’ bagi sebagian orang-orang Lebak. proses pemenuhan kebutuhan hidup mulai bergantung pada moda ekonomi tambang. Kebutuhan sandang, pangan, papan hingga menyekolahkan anak dihasilkan dari hasil tambang emas.
Resiko
Sebagian besar lokasi tambang rakyat berada didalam Zona inti pertahanan ruang hidup Lebak, sebagai sumber penghidupan orang lebak dan habitat bagi flora dan fauna, yang dilindungi. Pegunungan Sanggabuana/Halimun Salak. Bagi orang Lebak, Zona ini, berpungsi sebagai penopang sumber penghidupan Orang Lebak, dimasalalu, sebagai wilayah penghasil air, penghasil tumbuhan obat, tempat berburu dan tempat berladang. Zona inti ini, oleh sebagian kalangan juga di sebut sebagi zona penyangga, yang dalam istilah baru setelah adanya konsep Nation-state, disebut sebagai wilayah kehutanan . Didalamnya, hidup orang-orang pegunungan Lebak.
Dari zona penyangga ini, mengalir tak kurang dari 15 (lima belas) sungai besar, yang mengalir melewati perkampungan-perkampungan hingga perkampungan di wilayah pesisir, diantaranya:
- Sungai Cibareno
- Sungai Cisawarna
- Sungai Cipanengah
- Sungai Cimadur
- Sungai Cidikit
- Sungai Cimancak
- Sungai Cisiih
- Sungai Cimandiri
- Sungai Cihara
- Sungai Cipager
- Sungai Cilangkahan
- Sungai Ciwanasalam
- Sungai Ciliman
- Sungai Ciujung
- Sungai Ciberang
Keberlangsungan Sungai-sungai di atas, berdampak penting terhadap sumber penghidupan bagi orang-orang yang berada di hilir sungai, yang hidup dipinggiran sungai dan orang-orang yang hidup di pesisir, sebagai nelayan. Sungai-sungai ini, menjadi penghubung antara “Zona penyangga” dan “Zona Alas” yaitu wilayah pesisir Banten.
Aktivitas pertambangan pada “Zona penyangga” yang sudah berjalan sejak masa Kolonial Belanda, berlanjut pada masa PT ANTAM dan hingga Tambang Rakyat, kini. Sedikit demi sedikit, menggerus stabilitas Ruang Hidup Lebak, dari “Zona Penyangga” di wilayah hulu/pegunungan hingga “Zona Alas” di wilayah pesisir. Pembuangan limbah pertambangan, mencemari, meracuni, lahan-lahan pertanian, udara, sungai-sungai yang mengalir ke hilir dan berujung pada pencemaran laut. Selanjutnya, pecemaran terjadi pada tumbuhan, hewan dan manusia akibat dari basis inti dari alam yang telah teracuni. Tidak menutup kemungkinan, kepunahan tumbuhan langka, kepunahan binatang langka dan cacat fisik terhadap manusia akan terjadi.
Selain pada hal diatas, keselamatan dalam melakukan pertambangan, orang Lebak harus memiliki resiko kehilangan nyawa. Sebab, untuk mendapatkan batuan yang mengandung emas, harus menggali lubang tambang hingga belasan sampai puluhan meter ke dalam bumi. Kekuatan lubang tambang, hanya diperkuat dengan “steg-steg” yang terbuat dari kayu, untuk memperkuat lubang tambang agar tidak terjadi longsor atau runtuh pada lubang tambang. Kemudian, untuk memproduksi pertambangan rakyat skala kecil memerlukan minimal Rp.10.000.000, dengan hasil yang belum pasti. Tak jarang, beberapa penambang mengalami kerugian yang sangat besar hingga ratusan juta rupiah.
Selanjutnya, banyak penambang rakyat yang terlilit hutang, bahkan untuk makan saja sulit. Hal ini, digambarkan pada pribahasa yang dituturkan oleh salah seorang warga Cisungsang, “Imah gedong, beuteung lengkong. Imah butut beuteng samutut” . Namun, pada sebagian orang Lebak, keberhasilan sebagai penambang rakyat terjadi. Dari hasil tambang emas, beberapa orang Lebak mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Persoalan lain yang akan dihadapi oleh masyarakat penambang selain resiko-resiko yang dijelaskan adalah, ketidakberpihakan regulasi pemerintah Kabupaten lebak maupun provinsi Banten, umumnya pemerintah pusat. Karena, masyarakat penambang, melakukan kegiatan pertambangan di wilayah kehutanan, yang sering menghambat kegiatan pertambangan rakyat dengan alasan legalitas. Tak jarang, beberapa penambang ditangkap oleh aparat dengan alasan melakukan pertambangan tanpa ijin (illegal), sehingga harus di tangkap dan dibui. Seperti yang terjadi pada duaorang penambang rakyat di wilayah kecamatan Cibeber, beberapa waktu yang lalu. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi perusahaan besar yang dengan leluasa menguras sumber alam dengan dukungan ijin dari pemerintah. Beberapa perusahaan yang pernah melakukan ekspansi ruang hidup dikabupaten lebak diantaranya: PT. Rahmat Mas Pahala, PT. Darmabakti Cireundeu, PT. Baruna Guna Arta, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Sumber Alam Cipta Nusantara, PT. IMM, dan PT. MUK.
Penutup
Keterhubungan relasi manusia dan alam sedikit demi sedikit mulai terkikis, menjauh, diakibatkan dengan perubahan moda ekonomi “Organik” atau pemenuhan kebutuhan hidup dengan bertani, berburu, dan meramu dengan alat tradisional, warisan masalalu. Yang kemudian, bertransformasi menjadikan pertambangan sebagai mata pencaharian alternatif sebagian masyarakat. Lebih dalam pada persoalan ini, terjadi perubahan cara pandang pada sebagian orang-orang Lebak, yang pada awalnya masih percaya bahwa pertanian mampu menghidupi segala kebutuhan hidup menjadi bermental instan pada pilihan mata pencaharian. Hal ini, pada dasarnya merupakan hak bagi setiap orang lebak. Namun, terputusnya relasi manusia Lebak dengan alamnya mengikis kecerdasan-kecerdasan orang Lebak yang dihasilkan dari hubungan orang lebak dengan alamnya selama berabad-abad. Di masa lalu, orang Lebak mampu bertahan hidup dengan pengetahuan “Organik ” yang dimilikii oleh orang Lebak. hari ini, untuk bertahan hidup, orang Lebak, memerlukan berbagai macam peralatan yang rumit-rumit. Padahal, pada awalnya, orang Lebak mampu bertahan hidup hanya dengan kecerdasan tubuhnya.
Rangkasbitung, 2019