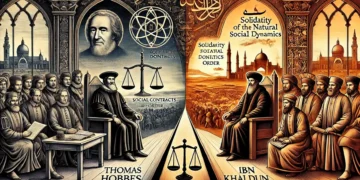Penulis adalah Ilham Nurul Azkiya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Dalam masa digital yang makin tumbuh, kemudahan akses terhadap layanan finansial jadi pedang bermata dua. Salah satu fenomena yang jadi sorotan publik dalam sebagian tahun terakhir merupakan menjamurnya layanan pinjaman online (pinjol). Di satu sisi, pinjol menanggapi kebutuhan warga yang kesusahan mengakses layanan perbankan konvensional.
Tetapi di sisi lain, kemudahan ini malah jadi jerat yang menyesatkan, bawa banyak pengguna pada suasana krisis finansial, apalagi psikologis. Dalam satu dekade terakhir, teknologi finansial tumbuh pesat serta menimbulkan bermacam inovasi, salah satunya merupakan layanan pinjaman online ataupun yang lebih diketahui selaku pinjol. Kemunculan pinjol awal
mulanya dikira selaku pemecahan inklusi keuangan, paling utama untuk warga yang tidak mempunyai akses terhadap layanan perbankan resmi.
Dengan proses yang kilat, ketentuan yang gampang, serta tanpa jaminan, pinjol jadi opsi utama banyak orang buat memperoleh dana praktis. Tetapi, di balik kemudahan itu tersembunyi kasus sungguh- sungguh yang lingkungan. Fenomena ini menimbulkan bermacam perkara hukum serta sosial. Tidak sedikit warga yang kesimpulannya terjerat utang sebab bunga besar, denda tidak normal, serta aplikasi penagihan yang melanggar etika. Apalagi, maraknya pinjol ilegal memperburuk keadaan, sebab beroperasi tanpa izin serta sering memakai cara- cara kekerasan dalam menagih utang.
Kemudahan yang Menjebak
Bayangkan, dengan cuma bermodalkan KTP, gambar selfie, serta smartphone, seorang dapat mendapatkan dana pinjaman dalam hitungan menit. Tidak terdapat jaminan, tidak butuh tatap muka, seluruhnya praktis. Tetapi, kenyamanan ini kerap kali mengaburkan kenyataan yang lebih hitam: bunga mencekik, denda tidak terbatas, serta metode penagihan yang
intimidatif. Banyak permasalahan menampilkan kalau peminjam dengan kilat tergelincir dari pinjaman awal ke pinjaman kedua, ketiga, serta seterusnya, sampai kesimpulannya mengunduh lebih dari 10 aplikasi pinjol dalam waktu pendek. Warga yang terbuai oleh kemudahan ini kerap tidak menyadari kalau sebagian besar pinjaman yang mereka ambil bukan buat kebutuhan produktif ataupun menekan, melainkan buat mengkonsumsi style hidup. Ini jadi pangkal dari siklus gali lubang tutup lubang yang berujung pada kegagalan bayar (galbay). Lebih tragis lagi, banyak dari mereka kesimpulannya jadi korban kekerasan verbal apalagi raga dari oknum debt collector yang dipekerjakan oleh penyedia pinjol, paling utama
yang ilegal.
Aspek Legal dan Perlindungan Konsumen
Dalam ranah hukum, posisi konsumen pinjol sepatutnya menemukan proteksi. Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas melaporkan kalau seorang tidak boleh dipidana penjara cuma sebab tidak sanggup penuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Maksudnya, kandas bayar pinjol, sepanjang tidak diiringi
dengan faktor penipuan ataupun hasrat jahat (dolus), tidak bisa dijerat pidana. Tetapi dalam praktiknya, banyak warga awam yang tidak menguasai perihal ini. Mereka sering kali diteror, diancam hendak dipidanakan, apalagi menemukan intimidasi menyangkut penyebaran informasi individu. Inilah yang jadi pelanggaran sungguh- sungguh terhadap hak konsumen, baik dari sisi etika ataupun hukum. Lebih jauh lagi, UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen pula
menegaskan kalau konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam memakai benda serta/ataupun jasa, dan berhak buat didengar komentar serta keluhannya. Hingga, aplikasi pinjol ilegal yang memakai kekerasan dalam penagihan jelas ialah pelanggaran terhadap hak- hak tersebut.
Tanggung Jawab Negara dan Peran OJK
Menyadari urgensi situasi ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai upaya, termasuk membentuk satgas waspada investasi dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindak pinjol ilegal. Per Desember 2021, OJK mencatat telah menutup lebih dari 3.500 entitas pinjol ilegal. Namun upaya ini belum cukup. Data OJK menunjukkan bahwa masyarakat masih terus menjadi korban. Sejak tahun 2019, jumlah pengaduan masyarakat atas praktik pinjol mencapai hampir 20.000 kasus. Di antara aduan tersebut, sekitar 47% masuk dalam kategori pelanggaran berat, termasuk pencairan dana tanpa persetujuan, penagihan dengan ancaman, hingga pelecehan seksual. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan pinjol ilegal adalah sifatnya yang lintas negara. Banyak aplikasi pinjol ilegal beroperasi dari luar negeri dan memanfaatkan celah hukum serta lemahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama internasional, pembaruan regulasi teknologi finansial, serta edukasi publik harus berjalan beriringan.
Konsumen: Korban atau Pelaku?
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya penempatan konsumen pinjol secara adil dalam kerangka hukum dan sosial. Tidak semua konsumen pinjol adalah korban yang tidak tahu menahu. Beberapa memang memiliki motif tidak baik, seperti meminjam tanpa niat membayar. Namun, mayoritas adalah korban dari sistem yang belum siap secara etika maupun hukum menghadapi disrupsi teknologi finansial ini. Bahkan, menurut analisis dari jurnal Res Justitia (2024), masyarakat kerap tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan pinjol ilegal. Minimnya literasi digital dan keuangan, serta tekanan kebutuhan ekonomi harian, mendorong mereka menerima syarat-syarat pinjaman yang sebenarnya melanggar hukum seperti bunga di atas ambang batas kewajaran dan perjanjian sepihak.
Solusi: Edukasi, Regulasi, dan Sosialisasi
Untuk keluar dari jerat ini, solusi tidak bisa hanya bergantung pada penindakan. Diperlukan strategi menyeluruh, mulai dari edukasi literasi keuangan di sekolah dan masyarakat, sosialisasi regulasi pinjaman legal, hingga kampanye publik untuk mengedukasi perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Pemerintah juga harus memberikan alternatif pembiayaan yang
mudah, cepat, dan legal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi digital berbasis syariah, atau sistem peer-to-peer lending berbadan hukum dapat menjadi solusi jangka panjang jika disertai pengawasan dan sistem edukasi yang tepat. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberi pelatihan khusus untuk membedakan antara
kasus perdata murni dan yang mengandung unsur pidana. Jangan sampai hukum dijadikan alat intimidasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan finansial.
Penutup: Menata Ulang Etika Konsumtif
Lebih dari sekadar persoalan hukum, maraknya pinjol mencerminkan krisis etika konsumtif di masyarakat. Keinginan instan, budaya pamer di media sosial, dan tekanan sosial-ekonomi mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Maka, perubahan juga harus datang dari dalam: membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya
hidup sesuai kemampuan, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta membudayakan gaya hidup hemat dan produktif. Kegiatan komunitas, seperti bercocok tanam, gotong royong, hingga pengajian dan seminar tentang bahaya pinjol, dapat menjadi benteng sosial yang efektif.
Sebagaimana disebutkan dalam jurnal Res Justitia, solusi sejati terletak pada sinergi antara masyarakat, negara, dan aparat hukum. Pinjol bukan hanya soal utang dan bunga, tetapi tentang masa depan etika dan perlindungan sosial masyarakat digital kita. Jika tidak ditangani dengan bijak, jerat ini bukan hanya menghisap dompet, tapi juga menggerus martabat manusia.