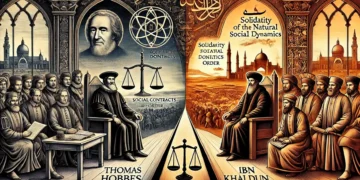Penulis : Farah Fadilla Putri, Alika Cahya Ramdhani, Neng Cahya Yulianti (Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Bina Bangsa).
Selayang Pandang
Anak merupakan anugerah titipan yang diberikan Tuhan YME kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Tetapi, pada realitanya sebagian anak-anak tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang semestinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 25 Ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Usaha pemerintah selama ini kayaknya cuma lip service aja deh. Iya sih, kadang-kadang mereka grebek pengamen jalanan, tapi besoknya anak-anak itu balik lagi ke jalan. Ada juga bantuan macem beasiswa atau kursus keterampilan, tapi itu nggak ngaruh banyak. Soalnya, masalah utamanya kan kemiskinan dan orang tua mereka yang nggak berdaya.
Sebenernya, pengamen cilik ini tuh korban. Orang tua mereka lagi susah duit, atau lebih parah lagi, ada mafia yang maksa mereka turun ke jalan. Miris banget kan? Harusnya mereka main-main, sekolah, eh malah harus ngamen. Belum lagi bahayanya, bisa kena kekerasan atau ketabrak mobil. Nasib mereka kayak gini gara-gara sistem yang nggak bener.
Pemerintah tuh perlu strategi yang lebih nge-hati dan nggak setengah-setengah. Pertama, bantuan sosial dan kerjaan buat keluarga miskin harus ditambahin. Masa sih, di negara sekaya kita, masih ada yang nggak bisa makan? Kedua, mafia yang manfaatin anak-anak buat duit mesti ditangkep, nggak ada toleransi. Ketiga, bikin rumah singgah yang bener. Bukan cuma kasih nasi sama kasur, tapi juga konseling biar mereka nggak trauma, plus pendidikan biar punya masa depan.
Ini bukan cuma tugas pemerintah loh, kita semua harus turun tangan. Jangan kasih duit ke pengamen anak, walaupun kasihan. Kenapa? Karena itu bikin mereka betah di jalan. Kasih duitnya ke yayasan anak jalanan aja. Atau kalau liat pengamen anak, telpon dinas sosial. Emang ribet, tapi cuma gini caranya biar anak-anak itu bisa balik ke habitat aslinya: rumah dan sekolah.
Latar Belakang
Kisah pengamen cilik di lampu merah bukan cuma drama jalanan, tapi cermin retak kebijakan pemerintah. Udah bertahun-tahun isu ini dibahas, dari era reformasi sampai era digital, tapi kok masih aja kita lihat anak SD nyanyi di warung makan bawa gitar kecil? Ini tanda, strategi pemerintah selama ini gagal total. Pemerintah kayaknya masih mikir ini cuma masalah setempat. Mereka kira, pengamen anak cuma urusan dinas sosial atau satpol PP. Jadinya, solusinya ya gitu-gitu aja: razia, tampung di panti, kasih makan, terus udah. Besoknya, anak-anak itu balik lagi ke jalan. Pemerintah lupa, ini bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga hati dan masa depan yang kelaparan.
Bantuan yang dikasih juga suka nggak nyambung, bro. Kayak program beasiswa. Niatnya sih oke, tapi anak yang udah bertahun-tahun nggak sekolah mana bisa langsung nyantol di kelas? Mereka butuh bimbingan all-out dulu. Atau contoh lainnya, diajarin bikin kue. Eh, selesai kursus, duitnya mana buat beli oven? Hasil akhirnya, si anak balik lagi deh jadi vokalis jalanan.
Koordinasi antar lembaga pemerintah juga parah. Dinas pendidikan sibuk nyusun kurikulum anti-bullying, tapi nggak nyambung sama dinas sosial yang tangani anak jalanan. Padahal, pengamen cilik sering jadi korban bullying. Atau, kementerian tenaga kerja fokus latihan skill buat fresh graduate, tapi nggak lirik buruh kasar yang anaknya ngamen karena upah nggak cukup.
Pemerintah juga sering lemah ke mafia yang memanfaatkan anak. Banyak sindikat mempekerjakan anak buat ngamen, bahkan ada yang dikirim antar kota. Ini udah masuk kategori human trafficking. Tapi apa yang terjadi? Paling banter cuma ditangkap calo kecil, bosnya bebas. Ini kayak bersihin lantai pakai sapu, tapi kran airnya tetep dibuka. Sayangnya, pemerintah lebih suka perbaiki gejala (kasih bantuan) daripada benerin sistem yang sakit.
Kita ambil contoh Kota Serang, ibukota Banten. Di sini, ada kawasan bisnis Banten Lama yang lagi ngetren. Hotel bintang lima, kafe hipster, mobil-mobil mewah parkir. Tapi coba deh, jalan dikit ke arah kampung Kasunyatan atau Kaloran. Banyak rumah semi-permanen, dan—yang bikin miris—banyak anak SD yang siap-siap bawa gitar ke Alun-alun buat ngamen.
“Nak, hari ini target 50 ribu ya,” ujar seorang ibu. “Kalau kurang, besok kita nggak bisa bayar listrik.” Ini pemandangan lazim di sana. Ortu, karena ekonomi terpepet, terpaksa jadiin anak sebagai “mesin penghasil duit”. Padahal, daerah lain di Banten kayak BSD City makmur banget. Ya gitu, yang miskin makin miskin, anaknya yang kena getah.
Banten itu miniatur Indonesia: modern tapi belum merata. Dan yang paling kena dampaknya? Anak-anak pengamen ini. Di balik suara merdu dan petikan gitar mereka, ada tangisan eksploitasi dan ketimpangan. Tiap recehan yang kita kasih, sebenernya menandai betapa gagalnya kita bagi-bagi kemakmuran. Banten punya potensi jadi provinsi maju, tapi kalau masih ada anak yang “dijual” demi nasi—sorry bro, itu bukan kemajuan, tapi kemunduran kemanusiaan. Isu pengamen anak ini sebenernya bisa jadi kasus studi yang hebat. Gimana kebijakan yang nggak manusiawi, nggak terintegrasi, dan nggak berbasis data, ujungnya cuma buang-buang duit rakyat. Pemerintah harus segera berbenah. Jangan sampai, 10 tahun lagi, kita masih ngomongin isu yang sama, dengan korban yang beda. Saat itu, anak yang dulu dipaksa ngamen, gantian maksa anaknya sendiri turun ke jalan. Lingkaran setan ini harus diputus, sekarang atau nggak sama sekali.
Topik Utama
Setiap kali kita lewat lampu merah dan melihat bocah kecil nyanyi sambil bawa gitar, apa yang terlintas? “Kasihan” atau “Lucu ya, pinter banget main musik.” Sayangnya, di balik pemandangan yang bikin hati trenyuh ini, ada bom waktu sosial yang siap meledak. Pengamen cilik yang kita beri recehan hari ini, besok bisa jadi “generasi gagal” yang bikin Indonesia goyang.
Pertama, soal kekerasan. Anak-anak ini bukan cuma nyanyi, mereka berjuang bertahan hidup di “hutan beton”. Dan di hutan, yang kuat memangsa yang lemah. Anak pengamen sering jadi bulan-bulanan. Ada yang ditampar gara-gara dianggap berisik, ada yang ditendang karena “menghalangi jalan”. Belum lagi kalau ketemu preman, bisa diperas sampai 50% penghasilan. Yang cewek? Satu dari tiga pernah dilecehkan. Iya, dilecehkan, di usia yang harusnya main boneka. Kekerasan ini bukan cuma bikin badan sakit, tapi juga jiwa. Anak-anak ini tumbuh dengan pikiran, “Dunia itu kejam, yang kuat yang menang.” Besok pas dewasa, apa yang terjadi? Tepuk tangan meriah buat pengamen cilik yang sukses jadi pengusaha? Bisa. Tapi yang lebih mungkin, dia jadi orang dewasa yang gampang marah dan main tangan. Ingat, hari ini korban, besok jadi pelaku. Satu generasi yang terbiasa disakiti, bisa jadi satu generasi yang senang menyakiti.
Lalu, ada masalah psikis dan biologis. Otak anak itu luar biasa, tapi perlu “pupuk” yang tepat: belajar, bermain, interaksi positif. Anak jalanan dapat apa? Polusi, makian, dan tekanan dapat duit. Hasilnya? IQ bisa turun 10-15 poin. Mereka juga sulit fokus, kebanyakan stimulasi negatif. Coba tonton pengamen cilik, matanya awas ke sana-sini, takut ditilang atau ditodong.
Secara emosi, mereka seperti rollercoaster. Ceria dapat uang banyak, marah-marah saat diusir. Nggak heran, orang dewasa yang dari kecil ngamen sering punya mood swing ekstrem. Susah juga mereka percaya orang atau menjalin hubungan dekat. Wong dari kecil diajari, “Jangan mudah percaya, nanti ditipu!”
Badannya? Banyak yang kena stunting, padahal bukan gara-gara gen, tapi karena kurang gizi. Menu mereka gado-gado nggak seimbang: kadang nasi padang, kadang cuma permen. Paru-paru mereka juga sering bermasalah, tiap hari nyedot asap knalpot. Yang horor, 1 dari 4 kena tinnitus—denging di telinga—gara-gara teriak-teriak di jalan bising.
Nah, ini yang paling bikin miris: kita punya “generasi gagal” dalam proses. Dari pengamen cilik di lampu merah, 70% putus sekolah. Begitu besar, 90% nggak balik ke sekolah. Bahkan yang masih bertahan, cuma 5% yang bisa baca lancar. Lulus SMA aja susah, apalagi kuliah. Boro-boro S1, ngisi formulir aja banyak yang bingung.
Waktu udah gede, mereka kayak “alien” di masyarakat sendiri. Susah gaul, soalnya punya stigma “anak jalanan”. Banyak yang akhirnya nyari “keluarga” di geng atau malah nyoba narkoba. Nyari kerja? Jangan ditanya. Komunikasi formal aja kagok, gimana mau interview? Alhasil, 80% terjebak di sektor informal. Yang naas, banyak yang tetap miskin dan—ini yang bikin hati mencelos—ngajak anaknya turun ke jalan juga. Lingkaran setan berlanjut.
Dampaknya ke bangsa? Gede, bro. Bayangin, 10 atau 20 tahun dari sekarang. Ribuan orang dengan trauma masa kecil, minim pendidikan, dan dendam ke sistem. Mereka nggak cuma jadi beban ekonomi, tapi juga ancaman sosial. Apatis dalam politik: “Pilih siapa juga, gue tetep miskin.” Ada juga yang radikal, merasa negara nggak adil. Di pilpres mendatang, jangan kaget kalau banyak mantan pengamen yang jadi sasaran empuk politik uang atau bahkan pesan ekstremis.
Jadi inget kata bijak: “Anak-anak adalah 20% populasi kita, tapi 100% masa depan kita.” Pengamen cilik yang kita abaikan hari ini adalah bom waktu sosial. Kita nggak cuma gagal melindungi mereka dari kekerasan atau eksploitasi. Kita juga—lewat kelalaian kita—menciptakan “generasi gagal” yang berpotensi mengacaukan Indonesia di masa depan.
Inilah mengapa kebijakan soal pengamen anak bukan cuma “proyek sosial”, tapi “pertahanan nasional”. Tiap anak yang kita selamatkan dari jalanan adalah investasi untuk negara yang lebih stabil, makmur, dan damai. Kalau nggak, suatu hari nanti, saat melihat kerusuhan atau terorisme di TV, jangan kaget kalau pelakunya adalah mantan pengamen cilik yang dulu sering kita beri recehan.
Catatan
Sobat, coba deh buka dompet. Ada recehan kan? Nah, recehan itulah yang bikin pengamen cilik terus bertahan di jalanan. Iya, nggak salah baca. Setiap kita ngasih duit ke anak pengamen, sebenernya kita lagi “mensponsori” penghancuran masa depan mereka. Berat ya? Tapi inilah realita yang harus kita hadapi.
Udah lebih dari dua dekade, pemerintah pake cara yang itu-itu aja buat atasi masalah pengamen anak. Razia, bawa ke panti, kasih makan, terus pulangkan. Atau kasih bantuan yang kayaknya wah—beasiswa, pelatihan keterampilan—tapi ujungnya nggak nendang. Hasilnya? Hari gini, kita masih aja nemuin anak SD ngamen.
Pola kebijakannya tuh kayak gini: ada pengamen → tangkap → kasih bantuan → lepas → jadi pengamen lagi. Muter-muter, tapi nggak maju-maju. Ini kayak kita ngasih plester ke orang patah kaki. Keliatan peduli, tapi nggak ngaruh apa-apa. Kenapa sih pemerintah ngotot pake cara yang udah proven gagal? Apa karena gampang? Atau karena takut ambil risiko?
Coba kita balik pertanyaannya: kenapa sih anak-anak itu ngotot ngamen? Jawabannya simpel: karena menghasilkan! Coba deh tanya pengamen cilik, “Dek, sehari dapet berapa?” Mereka bisa jawab, “Kadang 50 ribu, Kak, kalau hari libur bisa 100 ribu.” Sekarang, bandingin sama orang tuanya yang kerja di pabrik, sehari cuma 80-100 ribu. Ngamen lebih gampang, dan kadang lebih untung!
Nah, ini nih alasan kita butuh gerakan #JanganKasihReceh. Intinya gini: kita, masyarakat, setop ngasih duit ke pengamen anak. Bukan karena pelit atau jahat, tapi karena sadar bahwa recehan kita itu sebenernya racun. Recehan itulah yang bikin ortu mikir, “Wah, anak gue lumayan nih gajinya, besok ngamen lagi aja.” Tanpa sadar, kita ikut mengeksploitasi anak!
Pemerintah harus gerak cepat pas kita mulai gerakan ini. Begitu insentif ngamen ilang, harus ada “pengganti” yang lebih baik dan legal. Contoh: 1). Beasiswa yang bener: Bukan cuma uang sekolah, tapi juga uang jajan, buku, seragam. 2). Skill yang realistis: Jangan diajarin bikin kue doang, tapi sekalian dimodalin buka warung. 3). BLT Plus: Selain bantuan tunai, ortu juga dapat pendampingan wirausaha.
Inti gerakan #JanganKasihReceh ini sebenernya “tough love”. Sakit dikit, tapi demi kebaikan. Kayak ortu yang nggak mau beliin anaknya game online—bukan karena benci, tapi karena sayang. Sama kayak kita yang nggak ngasih duit ke pengamen cilik. Bukan karena pelit, tapi karena kita mau mereka punya masa depan yang lebih cerah.
Pemerintah udah lama mainin peran “ortu baik hati” yang ngasih duit jajan tanpa batas. Ujungnya, si anak (dalam hal ini, para pengamen) jadi manja dan nggak berkembang. Sekarang waktunya pemerintah jadi “ortu bijak” yang berani tegas. Ya, mungkin si anak bakal ngambek—protes, demo, teriak-teriak di medsos. Tapi nggak apa-apa, karena kita tau, ini demi masa depan mereka.
20 tahun lebih pemerintah ngasih “plester” ke pengamen anak. Bantuan sana-sini, tapi nggak pernah nyembuh. Sekarang waktunya operasi—dengan gerakan #JanganKasihReceh sebagai pisau bedahnya. Sakit? Iya. Berisiko? Jelas. Tapi antara operasi yang berisiko atau terus hidup sakit-sakitan, mana yang lo pilih?
Sobat, tiap kali kita kasih recehan ke pengamen anak, kita sebenernya ngasih mereka tiket VIP—Very Impoverished Person. Tiket buat tetap di garis kemiskinan. #JanganKasihReceh bukan gerakan pelit, tapi gerakan peduli yang berani. Kita percaya, anak-anak kita lebih pantes dapat beasiswa daripada recehan, lebih layak pegang pensil daripada ukulele.
Ayo, mari kita paksa pemerintah ubah kebijakan yang udah karatan itu. Bukan dengan teriak-teriak doang, tapi lewat gerakan konkret #JanganKasihReceh. Saatnya kita, rakyat, yang ambil kendali—demi masa depan anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih adil.
Rujukan
(STRATEGI BERTAHAN HIDUP ANAK JALANAN Anak dkk., 2009)
(EKSPLOITASI ANAK TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN ANAK 33-Article Text-165-1-10-20211122, t.t.)
(PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN, di KOTA MAKASSAR 1591-Article Text-2684-1-10-20170330, t.t.)