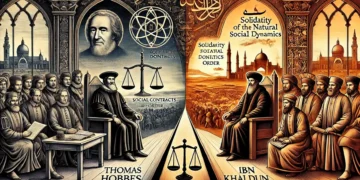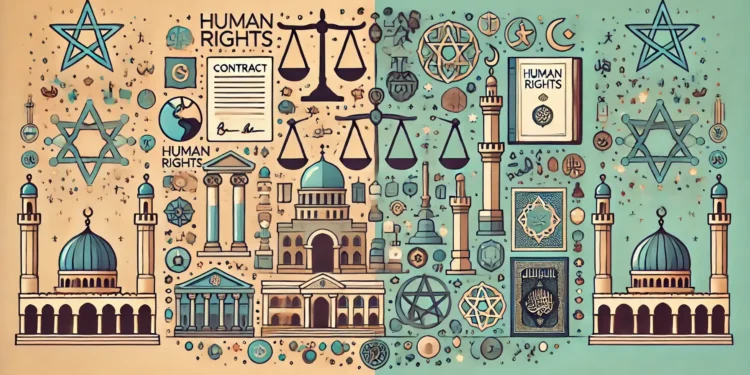Proses terbentuknya negara merupakan suatu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai pemikiran,nilai,dan sistem yang berkembang diberbagai belahan dunia. Pemikiran barat dan pemikiran muslim mengenai negara memiliki perbedaan yang mendalam,baik dalam hal konsep,legitimasi kekuasaan, maupun peran agama dalam kehidupan bernegara.pemikiran barat yang banyak dipengaruhi oleh teori-teori negara seperti yang dikemukakan oleh plato,aristotle,hobbes,locke,dan rousseau, cenderung menekankan pada prinsip-prinsip kontrak sosial,hak asasi manusia,dan pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan pemikiran muslim tentang negara berakar pada ajaran-ajaran islam yang tercermin dalam al-Qur’an dan hadis, serta praktek-praktek pemerintahan yang pernah diterapkan pada masa kekhalifahan. Dalam tradisi ini, negara dipandang sebagai institusi yang tidak terpisahkan dari kewajiban agama, dengan pemimpin yang diharapkan mampu menjalankan amanah dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum syariat.
Pendahuluan
Proses terbentuknya negara merupakan salah satu tema yang kaya dan kompleks, mencakup berbagai aspek dari sejarah, filosofi, politik, dan budaya. Dalam perspektif ini, terdapat dua aliran pemikiran yang sering diperdebatkan dalam literatur politik, yaitu pemikiran Barat dan pemikiran Muslim. Keduanya menawarkan pandangan yang berbeda tentang dasar-dasar pembentukan negara, tujuan, dan cara negara berfungsi dalam masyarakat. Pemikiran Barat tentang negara modern sangat dipengaruhi oleh tradisi filsafat Yunani kuno, pemikiran Romawi, serta perkembangan revolusi politik dan sosial di Eropa, terutama selama zaman Pencerahan (Age of Enlightenment). Di Eropa, negara dianggap sebagai entitas yang terbentuk melalui kontrak sosial, di mana individu-individu membentuk negara untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas kebebasan dan properti pribadi. Pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menyumbang pada teori kontrak sosial, dengan ide bahwa negara harus didirikan melalui kesepakatan atau perjanjian antara individu dan otoritas yang berkuasa. Di sisi lain, pemikiran Muslim mengenai negara terbentuk melalui prinsip-prinsip yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antara agama dan politik, dengan keyakinan bahwa negara seharusnya mengimplementasikan ajaran-ajaran agama sebagai bagian dari kehidupan sosial. Konsep ini dikenal dengan istilah “Imamah” atau “Khilafah”, yang merujuk pada kepemimpinan politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pemikir-pemikir Muslim klasik, seperti Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Al-Mawardi, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran politik Islam, dengan penekanan pada keadilan, musyawarah (shura), dan kepemimpinan yang berdasarkan pada ketaatan kepada Tuhan.
Perbedaan mendasar antara kedua pemikiran ini terletak pada pandangan mereka mengenai otoritas dan legitimasi negara. Pemikiran Barat sering kali memandang negara sebagai institusi sekuler yang terpisah dari agama, sedangkan dalam pemikiran Muslim, negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karena negara dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan hukum Allah. Pemikiran Barat dan Muslim tentang negara ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori-teori politik global. Perbedaan keduanya sering kali menjadi bahan diskusi dan refleksi dalam memahami tantangan modernitas, secularisme, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bernegara.
Unsur-unsur Terbentuknya Negara
adanya empat unsur yang menjadi kualifikasi sebuah negara sebagai subjek hukum internasional
Penduduk tetap, Syarat “tetap” dalam unsur ini bisa diartikan dalam 2 hal. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu (sebagai tempat tinggal) dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada dasarnya tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah minimum penduduk untuk membentuk suatu negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan.
Wilayah, Tidak ada ketentuan yang pasti berapa luas minimum suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu unsur yang membentuk sebuah negara.
Pemerintahan, Menurut Crawford juga, persyaratan bahwa sebuah negara yang dianggap ada mempunyai pemerintahan yang efektif bisa dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal. Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif, yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum.
Kedua, dengan menggunakan prinsip efektivitas, kriteria pemerintahan menunjuk kepada makna “pemerintahan yang efektif” yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pembentukan lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah terbentuknya negara yang bersangkutan.
Kemampuan Untuk Menjalin Hubungan Internasional Dengan Negara Lain
Sebagian ahli menyebutkan bahwa syarat yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif, dan bukan unsur konstitutif terbentuknya suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendiriannya. Bahkan, syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk organisasi internasional, termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi.
Keempat unsur tersebut sering disebut dengan the traditional criteria. Hal serupa disampaikan oleh Soehino dalam Ilmu Negara, syarat ada daerahnya yang tertentu, ada rakyatnya, dan ada pemerintahan yang berdaulat adalah syarat formal suatu negara, bukan syarat materiilnya.
benturan dari identitas peradaban yang berselisih, yang sangat mencolok antara Barat dan Islam. Teori Hegemoni Dalam Webster’s New Collogiate Dictionary disebutkan, bahwa kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani, hegemonia yang berarti pemimpin. Jadi, sama halnya dengan sifat umum yang terkait dengan pemimpin, maka hegemoni memiliki kata kunci: “pengaruh” dan “otoritas”. Konsep hegemoni mula-mula diperkenalkan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni adalah kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa (the ruling class). Menurut Gramsci, unsur esensial paling banyak mengenai filsafat modern tentang praksis (terkait dengan pemikiran dan tindakan) adalah, konsep filsafat sejarah “hegemoni”. Gramsci menolak ide perkembangan sejarah yang bersifat determinis atau “yang pasti terjadi” . Hegemoni menunjuk pada sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain. Dalam konteks politik internasional misalnya, pada periode Perang Dingin, pertarungan-pertarungan antara negara adikuasa, seperti Amerika Serikat dengan bekas Uni Soviet (Rusia sekarang), biasanya disebut sebagai perang untuk merebut kekuatan hegemoni dunia .
Gramsci membedakan antara hegemoni dengan kekuatan (force). Jika kekuatan meliputi penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, maka hegemoni meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pabotinggi, bahwa hegemoni menekankan pada dominasi ideologis/ politis atas kaidah-kaidah moral dan intelektual yang berlaku. Hegemoni, melalui produk-produknya, menjadi penentu satu-satunya dari apa yang dipandang benar secara moral maupun intelektual.
Hegemoni adalah dominasi sosial dimana “arah lain senantiasa didiamkan dan dilenyapkan dari diskusi, diperlakukan sebagai tak ada”. Menurut Pabotinggi, superaioritas Barat atas segala sesuatu yang “bukan Barat” merupakan pesan tunggal. Salah satu menifestasi terkuat dari hegemoni kultural-ideologis ini ialah diskursus Barat yang disebut dengan orientalisme. Strategi orientalisme tergantung secara konstan pada superioritas Barat yang dapat diwujudkan dalam berbagai posisi yang selamanya menempatkan superioritas Barat atas Timur. Mengutip Binder, Martin mengungkapkan, bahwa dalam studi Timur Tengah kebanyakan orientalis Barat memiliki prasangka negatif terhadap Islam.
Seberapa seriuskah prasangka tersebut menggerakkan keinginan untuk mengkaji Timur Muslim? Apakah pengaruhnya terus berlanjut pada mereka yang mengajar studi Timur Tengah sekarang?
Jawaban provokatif atas pertanyaan ini diberikan oleh Edward W. Said dalam karyanya, Orientalism. Menurut Said, “studi ketimuran” sebagai disiplin keilmuan secara material dan intelektual terkait dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa, dan orientalisme telah menghasilkan “gaya pemikiran yang dilandaskan pada distingsi teologis dan epistemologis antara “Timur” dan “Barat” dalam banyak hal. Said melanjutkan, bahwa orientalisme Barat mengembangkan cara-cara “pembahasan” tentang Islam (khusunya Arab) sehingga memapankan dan menyempurnakan rasa superioritas budaya Barat atas budaya lain. Said juga melihat adanya bias dalam tulisan-tulisan para sejarawan kolonial, misionaris, dan sarjana Barat. Bias yang paling populer menurut Said adalah proyeksi media tentang Arab saat ini sebagai masyarakat yang terbelakang, rasional dan penuh nafsu birahi.
Pencandraan (citra negatif) yang dibangun oleh Barat dalam menilai Timur itu sudah sedemikian kuatnya, sehingga Barat dikonotasikan sebagai kemajuan, desentralisasi, stabil, sementara Timur identik dengan stagnasi, sentralisasi, kacau dst. Terkait dengan teori di atas, Fuller mengatakan, bahwa benturan antar peradaban bukan antara Yesus Kristus, Konfusius atau Nabi Muhammad sebagaimana yang dipahami Huntington, tetapi bersifat ideologis. Peradaban adalah kendaraan bagi pengungkapan konflik, bukan penyebabnya. Kondisi yang mencerminkan dunia pasca runtuhnya komunis adalah dominasi (hegemoni) pandangan dunia Barat dalam ruang lingkup ekonomi dan politik yang didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu: pertama, kapitalisme dan ekonomi pasar.
Kedua, hak-hak asasi manusia dan demokrasi sekular-liberal. Ketiga, negara kebangsaan sebagai kerangka bagi hubungan internasional. Fuller berharap munculnya sebuah ideologi di Dunia Ketiga yang menentang nilai-nilai Barat. Menurut Fuller, jalan ideologi yang akan datang melawan Barat tergantung pada tipe para pemimpin yang muncul sebagai pembela kepentingan negara. Fuller menempatkan Cina, India, Iran, Mesir, Rusia (termasuk Indonesia, Brazil dan Afrika Selatan) di bagian depan daftar negara yang dipastikan memainkan peran utama dalam perjuangan ideologis melawan hegemoni Barat. Dikotomi Barat-Islam dewasa ini mencuat kembali menurut Munoz (dalam Esposito), karena akibat persepsi yang timbul dari pembagian dunia pasca-Perang Dingin ke dalam Timur dan Barat. Dalam pencariannya terhadap lawan baru sejak akhir tahun 1980-an, Barat telah memilih untuk melawan Islam, dengan mengangkat kembali isu-isu budaya sebagai pemicu konflik.
Mengutip Arkoun, Munoz menjelaskan, bahwa menguatnya persepsi dikotomis Barat-Islam karena adanya interpretasi historis yang difokuskan pada prinsip ideologi antagonisme (misalnya: Bizantium vs Kekaisaran Islam, Kerajaan Kristen vs Andalusia, Turki Usmani vs Eropa, Nasionalisme Arab-Islam vs Barat dst.). Persaingan hegemoni politik dan ekonomi antara dunia Kristen Abad Pertengahan dan Kekaisaran Arab-Islam ditafsirkan sebagai sebuah konfrontasi antarperadaban, yang menyebabkan kesadaran Barat memahami Islam sebagai lawan atau musuh. Sementara Kristen dan Yudaisme terintegrasi dengan Barat ke dalam peradaban Yudeo-Kristen, sedangkan Islam terpinggirkan. Prasangka-prasangka yang diciptakan oleh konfrontasi Islam dan Kristen di Spanyol dalam perang Salib atau perang melawan Turki merasuki kesadaran Barat secara mendalam. Di sinilah yang disebut oleh Munoz sebagai “kesalahan penafsiran sejarah”. Secara metodologis ada kecenderungan yang salah di kalangan para peneliti dan analis yang mengukuhkan ideal-ideal Barat sebagai satu-satunya patokan (bencmark) dan menempatkannya secara berbeda dengan ideal-ideal Islam.
Kecenderungan ini mengimplikasikan adanya simplifikasi atas perkembangan politik dan sosial di dunia Muslim dan menganggapnya sebagai tanda-tanda dari religiusitas yang ekstrem. Sekadar contoh, Revolusi Iran diasumsikan oleh Barat sebagai sebuah ungkapan fanatik dari cita rasa keagamaan, dengan mengabaikan semua faktor sosial, politik dan ekonomi yang menimbulkan gerakan revolusioner. Untuk alasan yang sama, fenomena Islam direduksi menjadi pemaksaan religius yang tidak rasional dan juga tidak dipertimbangkan mengapa ia muncul dan menyebar ke masyarakat, atau berpaling dari tatanan tradisional dalam pengertian sosiologis. Terorisme dan perang saudara, ketika melibatkan kaum Muslimin cenderung dijelaskan sebagai konsekuensi Islam itu sendiri (yang inheren dengan ajaran jihad-nya), bukan sebagai akibat dari setting politik dan sosio-ekonomi. Dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika jauh dikhawatirkan ketimbang Uni Soviet, karena pengaruh budaya dan ekonominya Amerika jauh melampaui Uni Soviet. Demikian pula, pasca Perang Dingin (Cold War), Amerika juga menganggap ideologi kelompok fundamentalis Muslim merupakan tantangan yang jauh membahayakan. Pendeknya menurut Daniel Pipe, Amerika harus menghadapi rintangan yang lebih besar di bawah kelompok fundamentalis.
Dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika dan sekutu-sekutunya, memiliki pengaruh budaya yang amat luas, misalnya: bahasa, gaya hidup, media massa (BBC, program televisi, musik, video game, komik, teks book dan seterusnya). Pada wilayah agama misalnya, Amerika mengeksport dua hal: Kristen (sebagai rival Islam tradisional) dan sekularisme (sebagai rival modern). Missionaris Kristen merupakan bayang-bayang besar bagi kalangan fundamentalis Muslim. Perang Dingin (Cold War) sudah dianggap memori, tetapi Amerika masih menghadapi resiko tinggi yang mereka sebut dengan Green Peril. Green dikonotasikan sebagai warna Islam, sementara Peril disimbolkan sebagai Muslim fundamentalis Timur Tengah. Fundamentalis Muslim ini dianggap sebagai gerakan revolusi agresif, militan, dan garang sebagaimana Bolshevik, Fascist dan Nazi yang anti demokrasi, anti-sekuler, otoriter dan segala macam stigma buruk lainnya. Inilah Perang Dingin Baru (The New Cold War) yang disebut Jurgensmeyer. Memang tidak mudah untuk menunjuk siapa yang memulai membangun image antagonisme ini. Di satu sisi, sebagian kaum Muslimin memandang Barat sebagai koloni yang harus dilawan, dan juga sebaliknya pada sisi yang lain, Barat memandang kaum Muslimin sebagai ancaman yang harus dihegemoni. Kalau Bernard Lewis mempertanyakan, mengapa muncul kelompok-kelompok Islam yang anti Amerika atau Barat?
Padahal menurut Lewis, jika alasan mereka adalah karena persoalan kolonialisme dan imperialisme, maka tidaklah tepat, sebab Amerika tidak pernah menjajah negeri Muslim. Sebetulnya yang harus menuntut dan paling anti Amerika, menurut Lewis, adalah Vietnam dan Kuba yang memang dijajah. Alasan Lewis ini naif, karena ia hanya melihat penjajahan dalam bentuk fisik, dan cenderung apologetik, karena sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan para sekutunya (negera Barat) dalam menghegemoni Iraq misalnya, sudah sangat mencolok. Menurut pengamat politik Timur Tengah, Riza Syihbudi, bahwa tudingan Amerika terhadap kelompok garis keras (Islam) sebagai teroris merupakan lagu lama yang selalu diulang-ulang. Setiap ada kekerasan dan teror selalu dikaitkan dengan orang-orang Arab, Timur Tengah dan Islam.
Persoalan ini sudah menjadi opini publik yang dibangun melalui penguasaan media massa oleh kelompok Zionis Amerika. Bahkan kecurigaan itu kini sudah meluas ke Indonesia, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hegemoni Barat terhadap Islam di Timur memang sudah sedemikian kuatnya, sehingga memasuki relung-relung kehidupan: ekonomi, politik, budaya dan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Binder (Khalid bin Sayyed), bahwa tidak ada wilayah budaya yang mencemaskan mengenai ancaman penetrasi budaya dan peradaban, dan simbol sentral kegelisahan ini adalah Islam dengan otentisitas dan identitasnya. Dalam konteks relasi antara peristiwa musibah kemanusiaan di WTC, AS.
Machiavelli mengatakan, mengemukakan bahwa selain untuk mencari kekuasaan, tujuan negara adalah mempersatukan wilayah yang terpecah belah. Negara akan menciptakan kemakmuran dan persatuan. Pun demikian Immanuel Kant, tujuan negara adalah menegakkan hak dan kebebasan warganya. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu dalam negara itu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Untuk mencapai tujuannya, negara harus melakukan pemisahan kekuasaan dengan badan masing-masing yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Oleh: Siti Khodijah
Referensi
https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/hubungan-barat-islam.html
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/02000071/tujuan-negara-menurut-ahli